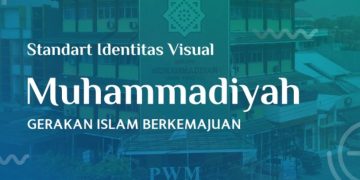Oleh: M. Husnaini*
Pimpinan dan aktivis Muhammadiyah di banyak tempat kerap mengeluhkan fenomena masuknya Salafi ke lingkungan Muhammadiyah. Salafi memang diakui memiliki banyak kemiripan dengan Muhammadiyah, terutama dalam pemurnian akidah dan ibadah. Namun, tidak sedikit fikih Salafi yang bertentangan, bahkan cenderung melemahkan dan menyalahkan Muhammadiyah.
Muhammadiyah memahami bahwa perbedaan fikih adalah lumrah. Menjadi masalah ketika fikih yang berseberangan dengan Muhammadiyah diajarkan dan diterapkan ke lingkungan jamaah Muhammadiyah. Organisasi selain Muhammadiyah, rasanya, juga menolak infiltrasi paham lain ke jamaahnya.
Dalam lingkungan Nahdlatul Ulama, misalnya, ada standarisasi kitab yang boleh dipelajari dan dijadikan referensi, dikenal dengan istilah al-kutub almu’tabarah. Pertanyaannya, mengapa paham lain, dalam konteks ini Salafi, masuk ke Muhammadiyah sehingga belakangan terkenal istilah Musa (Muhammadiyah-Salafi) atau Mursal (Muhammadiyah Rasa Salafi)? Selain kemiripan paham tentang akidah dan ibadah, menurut saya, sebab utama yang penting dijadikan introspeksi bersama adalah sikap permisif pimpinan Muhammadiyah sendiri.
Ketika mengadakan kajian rutin, misalnya, ada sebagian pimpinan Muhammadiyah yang justru mengundang mubalig non-Muhammadiyah. Jika untuk pengajian umum yang diadakan sesekali, barangkali dimungkinkan, apalagi jika pengajian umum tersebut membutuhkan kompetensi tertentu, dan di luar masalah paham keagamaan. Tetapi jika mengadakan kajian rutin di bidang tafsir, hadis, fikih, dan semisalnya, menggunakan mubalig non-Muhammadiyah, termasuk Salafi, sebagai pemateri adalah sebuah wujud keteledoran.
Muncul kesan seolah tidak ada mubalig Muhammadiyah yang kompeten—dan barangkali inilah fenomena yang umum. Kesan lain adalah lebih mengandalkan mubalig nonMuhammadiyah dibanding mubalig Muhammadiyah—dan kesan kedua ini juga tidak jarang terjadi. Melalui kesempatan mengisi kajian rutin tersebut, mubalig non-Muhammadiyah mula-mula tidak menunjukkan gelagat berbeda. Lambat laun, mubalig yang bersangkutan mulai mengomentari, dan bahkan menyalahkan putusan-putusan resmi Muhammadiyah.
Misalnya, lagu dan musik yang oleh Muhammadiyah dihukumi mubah, mulai dipermasalahkan. Rapat di Muhammadiyah yang tidak lekas diakhiri ketika terdengar azan, dikritik habis-habisan. Muhammadiyah dipersepsi tidak mengerti makna Allahu Akbar. Lebih jauh, dalam kajian tersebut bahkan ditegaskan bahwa pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah harus bertobat karena memilih hisab dibanding rukyat—mengingat hisab dipahami sebagai bidah.
Sikap Muhammadiyah yang sejak awal mendukung NKRI juga terus digoyang. Jamaah lalu digiring untuk mengharamkan Pancasila. Jihad hanya dimaknai dengan satu kata, yaitu perang. Istilah “mahasiswa” yang tidak bermasalah di kalangan Muhammadiyah kini disalahkan, karena “maha” itu copyright Allah dan haram untuk selain-Nya.
Bagi jamaah yang kritis, nuansa kajian rutin yang berubah tersebut langsung terasakan. Namun, jamaah yang memiliki literasi minim tentang Muhammadiyah segera mengamini semua pikiran mubalig yang bersangkutan dan menganggapnya sebagai putusan resmi Muhammadiyah. Tidak semua jamaah mampu membedakan antara pikiran pribadi dan putusan organisasi.
Bagi kaum awam, Muhammadiyah adalah segala yang dipikirkan dan disampaikan mubalig dalam kajian rutin yang memang diselenggarakan oleh Muhammadiyah tersebut. Dari sinilah sebenarnya pintu masuk Salafi, atau kelompok apa saja, ke Muhammadiyah. Karena itu, pimpinan Muhammadiyah, mulai ranting dan terlebih-lebih pusat, perlu lebih selektif dalam menentukan mubalig yang mengisi kajian rutin di lingkungan Muhammadiyah. Berlimpah ulama dan pakar dari kalangan intern Muhammadiyah. Kita tinggal pilih sesuai bidang keilmuan mereka sehingga tidaklah perlu mencari mubalig non-Muhammadiyah untuk mengampu kajian rutin keagamaan.
Sudah banyak buku ditulis untuk memberikan penjelasan bahwa Muhammadiyah tidak serupa dengan Salafi. Sebut saja buku Muhammadiyah dan Wahabisme (2013). Jauh sebelum itu, yaitu pada 1950-an, Buya Hamka menulis risalah kecil berjudul Teguran Suci & Jujur terhadap Mufti Johor untuk menegaskan bahwa Muhammadiyah bukan Wahabi.
Belakangan, terbit dua jilid buku bertajuk Titik Pisah Fikih Salafi-Muhammadiyah karya Ali Trigiyatno, yang lalu diringkas oleh Muhammad Utama Al Faruqi menjadi Perbedaan Muhammadiyah dan Salafi. Buku-buku tersebut penting ditelaah oleh mubalig dan jamaah Muhammadiyah, terlebih pimpinan Muhammadiyah dan pengelola AUM/A, supaya pemahaman Islam menjadi up to date dan tidak expired.
Kebiasaan membaca menjadikan pelakunya tidak gumunan. Selain beberapa dokumen resmi yang mengandung pemahaman ideologi, tidak kalah penting bagi mubalig Muhammadiyah mengasup wawasan tentang paham Muhammadiyah melalui Suara Muhammadiyah dan Suara Aisyiyah. Delapan jilid buku Tanya Jawab Agama dan dua jilid buku Himpunan Putusan Tarjih (HPT) jangan pula sampai dilewatkan.
Lebih bagus sekiranya masjid atau AUM/A memiliki koleksi referensi di atas untuk diletakkan di tempat yang mudah diakses. Dengan begitu, siapa saja dapat membaca ketika sewaktuwaktu memerlukan jawaban atas persoalan keagamaan. Mubalig yang hendak mengurai sebuah hukum juga dapat menjadikan buku-buku dan majalah-majalah tersebut sebagai rujukan, di samping kitab-kitab lain. Dengan begitu, selain bisa meng-update informasi aktual tentang Persyarikatan, pandangan keislaman jamaah, lebih-lebih mubalig Muhammadiyah, tidak bertentangan dengan fatwa dan putusan resmi Muhammadiyah.
Di sisi lain, upaya demikian diharapkan dapat menghidupi penerbitan di Persyarikatan, sekaligus menjadikan masjid dan AUM/A sebagai pusat literasi ilmu. Jangan sampai membiarkan jamaah Muhammadiyah awam tentang Islam dan Muhammadiyah. Lebih tidak pantas kalau mubalig Muhammadiyah tampil di atas mimbar Muhammadiyah menjelaskan hukum-hukum agama tetapi pendapatnya justru menyalahi sikap resmi Muhammadiyah. Karena mubalig bersangkutan biasanya dipersepsi sebagai tokoh Muhammadiyah, sudah selayaknya sikap dan pandangannya menjadi corong bagi fatwa dan putusan resmi Muhammadiyah. Sekali lagi, jamaah akar rumput berhak mendapatkan wawasan tentang Muhammadiyah secara memadai.
Keberadaan Muhammadiyah juga harus mendatangkan manfaat besar, utamanya bagi warganya sendiri. Harapan lebih jauh, berbagai kajian di masjid bisa dilanjutkan ke kehidupan nyata sehari-hari dengan berbagai ide dan terobosan pemberdayaan. Muhammadiyah tidak boleh hanya melahirkan kumpulan warga yang tidak produktif, tetapi malah terampil menampilkan Islam yang kaku, garang, dan serba haram. Warga Muhammadiyah harus merasa bangga menjadi warga Persyarikatan, dan tidak mudah dibuat pusing oleh “penyusup-penyusup” yang hanya ingin mengeruk massa lewat jamaah Muhammadiyah.
Dakwah Muhammadiyah itu moderat, sejuk, ilmiah, kreatif, serta jauh dari sikap-sikap radikal dan anarkis. Dakwah Muhammadiyah juga bukan dakwah yang sempit dan serba mengharamkan, melainkan dakwah yang menghidupkan lagi mencerahkan. Jadi, selain bersikap selektif untuk tidak membiarkan siapa saja mengisi kajian rutin keagamaan di lingkungan Muhammadiyah, kaderisasi mubalig Muhammadiyah sangat urgen. Perlu lebih banyak kader Muhammadiyah dengan kompetensi keilmuan memadai untuk terjun ke bawah, tidak hanya aktif di Muhammadiyah level atas.
Jangan lagi ada mubalig non-Muhammadiyah tampil dan menjadi rujukan jamaah Muhammadiyah karena faktanya memang tidak ada mubalig Muhammadiyah yang dipandang kompeten di akar rumput. Dengan semangat belajar dan membaca literatur-literatur resmi, Muhammadiyah secara kuat seperti disebutkan di atas, semoga kader-kader Muhammadiyah kian hari kian meningkat secara kuantitas dan kualitas. Dengan demikian siap terjun ke masyarakat untuk memberikan pencerahan seputar keislaman dalam kerangka pikiran dan putusan resmi Muhammadiyah yang berkemajuan.
*Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Daerah Istimewa Yogyakarta