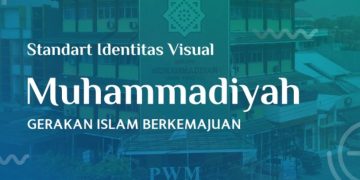Oleh : Muhammad Yunus, S.Ag.*
Beberapa bulan yang lalu ada beberapa agenda dan peristiwa politik yang mewarnai kehidupan demokrasi kita. Agenda politik ini variatif. Mulai dari agenda politik kenegaraan, agenda pertemuan (silaturahmi) tokoh dan elite politik, kebijakan politik yang menuai gejolak social dan sebagainya.
Agenda politik sering kali melibatkan aktivitas keagamaan, ritual spiritual maupun social kemanusiaan. Seringkali agenda politik menjadi kontroversial, meriuhkan percakapan publik di dunia maya maupun nyata. Dari berbagai agenda politik tersebut, ada sebuah peristiwa politik yang menuai sorotan tajam dalam percakapan publik. Peristiwa ini menuai sorotan tajam karena berkaitan dengan etika dan moralitas sebagai pejabat publik atau sebagai figure elite politik.
Dugaan pelanggaran etika yang dilakukan penyelenggara pemilihan umum dan dugaan bagi-bagi uang yang dilakukan politikus di tempat Ibadah adalah sebagian contoh. Bulan Ramadan yang seharusnya dijadikan momentum untuk meneguhkan moralitas dan keadaban setiap insan dalam lingkup kemasyarakatan, kebangsaan serta kemanusiaan.
Aktivitas politik kenegaraan dan kebijakan politik kenegaraan seharusnya mengedepankan keadaban, seperti nilai-nilai kebijaksanaan, kedamaian, kekhidmatan, ketundukan diri pada nilai-nilai kebaikan, kebenaran dan keadilan. Begitu halnya dengan figure elite politik. Manusia dan Agama memiliki relasi yang sangat kuat. Dengan itulah manusia disebut sebagai homo religiousus. Mercia Eliade adalah pencetus istilah itu. Homo religiousus adalah tipe manusia yang hidup dalam suatu alam yang sacral, penuh dengan nilai-nilai religiusitas, dapat menikmati sakralitas dan tampak pada alam semesta.
Pengalaman dan penghayatan tentang yang suci atau realitas mutlak (ultimate reality) memengaruhi, membentuk dan ikut menentukan corak hidupnya. Salah satu dimensi penting dalam ajaran Agama yang berkaitan dengan perilaku manusia adalah menjadi ajaran yang paling penting dalam beragama. Misi utama pengutusan Nabi Muhammad SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak. Begitu pentingnya dimensi akhlak dalam ajaran agama sehingga dalam suatu Hadist dikatakan bahwa puncak kesempurnaan dari keimanan seorang mukmin adalah terletak pada akhlaknya yang paling baik.
Agama adalah sumber ajaran moral. Ajaran moral ini dirumuskan menjadi nilai-nilai dan prinsip-prinsip luhur yang harus dipahami dan diaktualisasikan dalam berbagai aspek kehidupan. Kohesivitas agama dan moralitas merupakan sebuah keniscayaan. Karena ajaran Islam memiliki fungsi transformatif dalam mentransmisikan berbagai dimensi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Puasa Ramadhan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam.
Antroposentis dan Teosentris
Ibadah puasa Ramadan beserta seluruh rangkaian aktivitas yang dianjurkan di dalamnya memiliki banyak kandungan pesan moral. Dalam pemaknaan kebahasaan, puasa (al-shauma/al-shiyamu) bermakna dasar al-imsak yang berarti menahan dan at-tarku yang berarti meninggalkan. Term puasa secara syari’at adalah menahan diri dari makan dan minum serta pemenuhan hasrat biologi dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari.
Secara hakikat, makna puasa berarti menahan diri atau mengendalikan diri dari hawa nafsu duniawi yang seringkali melampaui batas dari manusia. Berdasarkan pemaknaan ini, dapat dipahami bahwa Ibadah puasa memiliki pesan dan symbol ajaran moral yang luhur. Hal ini sangat relevan yang dikemukakan Az-Zarqani bahwa didalam puasa itu terdapat tiga dimensi utama sekaligus, yakni dimensi kejiwaan (religion, psychological, ruhiyyah) yang bersifat transenden dan privat, dimensi moral (akhlaqiyah) dan dimensi kesehatan (medis).
Pemaknaan puasa ini dalam konteks moralitas politik seharusnya menjadi laboratorium untuk menahan serta mengendalikan diri dari tindakan-tindakan yang paradoksal dengan fitrah manusia yang selalu menjadi. Menahan dan mengendalikan diri dari perilaku flexing, arogan, kesombongan dan keangkuhan. Dalam arti yang lebih luas, puasa adalah medium membebaskan manusia dari tindakan-tindakan yang kontraproduktif dengan nilai-nilai kemanusiaan, seperti dominasi struktur yang menindas, diskriminasi, hegemoni, tirani dan sebagainya.
Puasa dalam konteks ini juga seharusnya menjadi medium untuk mengendalikan dan menahan nafsu-nafsu keduniawian yang paradoksal dengan nilai dan prinsip keadilan, seperti pembuatan kebijakan, produk politik atau diskresi yang tidak berpihak kepada orang-orang lemah, mempertimbangkan moralitas publik dan memperhatikan nilai kemaslahatan serta meminimalisir kemudaratan.
Dalam rangkaian Ibadah puasa terdapat kewajiban menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah ini berfungsi sebagai penyucian orang yang berpuasa dan sebagai keberpihakan kepada orang-orang miskin. Zakat adalah manifestasi kepedulian sosial yang melahirkan rasa empati kepada sesama dengan member. Tentu saja kepedulian sosial ini harus memiliki orientasi yang lurus, bukan justru menjadi ajang politisasi atau bahkan kapitalisasi. Ajang politisasi dalam arti memberi demi untuk menjulangkan eksistensi (popularitas) dan ketersukaan (elektabilitas). Zakat adalah pranata filantropis Islam yang merupakan menifestasi dari upaya memanusiakan manusia dengan menghilangkan kecintaan berlebih kepada kebendaan, ketergantungan pada materi, kekerasan dan kebencian dari dalam diri manusia.
Dalam konteks moralitas dan keadaban politik, segala kewenangan yang melekat pada pejabat public untuk membuat kebijakan harus memihak kepada orang-orang lemah dan tertindas, baik ketertindasan secara structural maupun ketertindasan secara cultural (mustadh’afin). Pertemuan elite politik yang dibungkus dengan agenda silaturahmi Ramadhan seharusnya menjadi momentum membahas hal-hal yang menyangkut pembelaan kepada mustadh’afin, keberpihakan kepada pencari keadilan dan memperjuangkan kepentingan serta kemaslahatan bersama.
Pelaksanaan Ibadah puasa tentu diharapkan menjadi laboratorium untuk melahirkan pribadi yang bertaqwa. Puasa Ramadan dan politik sesungguhnya memilik korelasi filosofis, yakni pencapaian spiritualitas konstruktif dan moralitas kolektif. Puasa Ramadan dan aktivitas politik memiliki komitmen moral yang kohesif. Pencapaian spiritualitas konstruktif dalam arti bahwa Ibadah puasa tidak mengepisentrumkan aktivitasnya hanya secara vertical kepada Sang Pencipta, namun juga ada peranan manusia sebagai pemimpin dimuka bumi ini yang mengelola dan memakmurkannya.
Demikian juga aktivitas politik yang tidak hanya memusatkan aktivitas pada dimensi antroposentris, melainkan perlu ada orientasi teosentris yang melibatkan Tuhan Yang Maha Esa dalam segala hal serta melandaskan aktivitas politik itu tetap pada nilai-nilai transcendental. Karena tentunya puasa juga diharapkan melahirkan kepribadian yang berakhlak, menjunjung tinggi moralitas, tak terkecuali moralitas politik. Dalam konteks moralitas politik ini untuk menjaga dan mempertahankan integritas seorang pemimpin, tentunya bisa direalisasikan nilai-nilai keprofetikan (kenabian) untuk menjaga integritas seorang pejabat atau seorang pemimpin. Hal ini seharusnya menjadi sebuah keinsyafan bersama, bahwa untuk menjaga integritas di dalam sebuah transformasi dari penanaman nilai-nilai etis yang akan berdampak pada etos kita
*Guru SMK Muhammadiyah 1 Undaan, Ketua PCPM Undaan, & Anggota Bidang Hikmah dan Kebijakan Publik PDPM Kudus