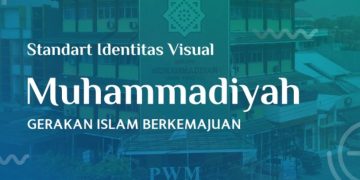Selama ini kita mengenal al-Qur’an sebagai cetakan mushaf yang menghimpun firman Allah Swt. Tapi kenapa ada istilah “turunnya al-Qur’an” kepada Nabi Muhammad? Apakah al-Qur’an turun dalam bentuk kitab cetakan? Tentu saja bukan.
Al-Qur’an sebagai kalamullah pada mulanya secara keseluruhan tersimpan di Lawhu al-Manfudz. Setelah itu, Al-Qur’an “turun” dalam dua proses sebagaimana keterangan dari Al-Zarkasyi dalam al-Burhan fi ‘Ulum al-Qur’an.
Pertama, diturunkan secara sekaligus dari Lawhu al-Manfudz ke langit dunia atau yang dikenal dengan sebutan Bayt al-‘Izzah pada malam Lailatul Qadr (QS. Al Qadr: 1).
Kedua, diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad Saw di bumi dalam rentang waktu 23 tahun yang disesuaikan dengan situai dan kondisi.
Mengapa Al-Qur’an turun Berangsur-angsur?
Dalam al-Itqan fî ‛Ulum al-Qur’an, Jalal al-Din al-Suyuthi mengungkapkan alasan mengapa Al-Qur’an turun kepada Rasulullah tidak secara menyuluruh. Menurutnya, agar menambah keyakinan dan keteguhan hati Rasulullah, memudahkan penghafalan dan pencatatan, dan adanya sebagian kecil ayat-ayat yang menghapus (nasikh) dan yang terhapus (mansukh). Turunnya Al-Qur’an kadang sebagai sebuah jawaban atas suatu masalah, atau juga sebagai kabar, berita, pengajaran, peringatan, dan nasihat tergantung situasi dan kebutuhan.
Ketika ayat-ayat Al-Qur’an itu disampaikan pada penduduk Mekkah atau Madinah, isi ayat-ayat al-Qur’an seringkali membawa perspektif atau informasi yang baru dan berbeda.
Sebagai contoh, al-Qur’an menekankan betapa pentingnya posisi dan mulianya derajat perempuan. Tergambarkan dengan jelas ketika al-Qur’an mengadvokasi urusan hak waris dan hak atas proteksi sosial bagi perempuan.
Penduduk Mekkah atau Madinah tahu bahwa perempuan punya posisi tertentu dalam masyarakat. Tapi seperti apa wujud konkret posisi perempuan secara bermartabat dan adil, tidak ada satu pun penegasan yang jadi mainstream di masyarakat.
Begitu pula dengan seruan moral dalam al-Qur’an untuk pengentasan kemiskinan, anak yatim, pembebasan budak dan bidang-bidang lainnya merupakan bukti upaya untuk menjawab problem kemanusiaan.
Dalam beberapa hadis, Rasulullah membeberkan bagaimana suasana batin saat wahyu itu turun kepada dirinya. Kadang Nabi Saw terasa seperti mendengar bunyi lonceng yang sangat kencang, atau Malaikat Jibril terasa seperti berbisik dalam sukmanya, dan tidak jarang pula didatangi langsung Malaikat Jibril sebagaimana dalam peristiwa di Gua Hira dan Isra Mi’raj. Kadang pula Rasulullah menerima wahyu dalam keadaan tidur melalui mimpi.
Acapkali wahyu itu turun, Rasulullah akan meminta para sahabatnya untuk menghafal dan menuliskannya dalam berbagai medium seperti papirus, pelapah kurma, kayu, dan lain sebagainya. Penulisan ayat-ayat al-Qur’an ini diyakini telah mulai sejak era Nabi di Mekkah. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam kisah yang cukup terkenal tentang masuk Islamnya ‘Umar bin Khattab setelah membaca lembaran QS. Thaha ayat 1-6. Usai membaca ayat tersebut, bergetar jiwa Umar dan memutuskan masuk Islam.
Al-Qur’an: dari Budaya Lisan ke Tulisan
Tapi penulisan Al-Qur’an secara lebih sistematis baru dimulai di Madinah, khususnya setelah Nabi secara resmi menunjuk beberapa sahabatnya untuk melakukan tugas ini. Mu’awiyah bin Abi Sufyan, Ubay bin Ka’ab, Zayd bin Tsabit, dan ‘Abdullah bin Mas’ud, adalah nama-nama yang biasa disebut sebagai penulis wahyu di Madinah.
Menurut al-Suyuthi dalam al-Itqan, lembaran-lembaran Al-Qur’an yang ditulis para sahabat ini memiliki jumlah dan susunan surah yang berbeda. Namun yang jelas, tidak disusun berdasarkan urutan kronologis ayat-ayat Al-Qur’an.
Dalam Kitab Shahih Bukhari terutama dalam “Fadhail Al-Qur’an” dijelaskan bahwa untuk menjauhkan dari kekeliruan, biasanya setiap malam di bulan Ramadan kadang juga di bulan yang lain, Malaikat Jibril mendatangi Rasulullah untuk mengulangi bacaan dalam rangka menjaga keaslian dan keutuhan Al-Qur’an baik dari segi susunan ayat maupun yang lainnya. Karenanya, bentuk bacaan Al-Qur’an pada masa Nabi memang telah ada dan telah sempurna jauh sebelum adanya Mushaf Utsmani.
Proses Kodifikasi Awal Al-Qur’an
Perbedaan jumlah surah dan yang lainnya di antara Sahabat itu disebabkan oleh berbagai faktor. Mushaf Ubay misalnya mengoleksi 115 surah, sementara Mushaf Ibn Mas’ud 108 surah, dan Mushaf Ibn `Abbas 116 surah. Hal ini wajar belaka sebab menurut Syamsuddin Arif, di antara mereka ada yang belum atau tidak tahu versi terakhir, belum atau tidak sempat mengoreksi naskah catatannya, belum atau tidak sempat menyalin ulang berdasarkan instruksi terakhir, serta meminta pengesahan dari Rasulullah.
Saat Nabi Saw wafat, seluruh Al-Qur’an telah lengkap dan sempurna. Tidak lama setelah itu, meletus perang Yamamah, yakni pertempuran yang melibatkan pasukan Khalifah Abu Bakar melawan orang-orang murtad, Nabi-nabi palsu, dan para pembangkang zakat. Meski meraih kemenangan, namun sejumlah para penghafal Al-Qur’an berguguran dalam pertempuran tersebut. Hal inilah yang membuat Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar agar segera mengumpulkan dan menghimpun catatan-catatan Al-Qur’an yang berserakan dalam suatu naskah utuh.
Zayd bin Tsabit yang terkenal cerdas dan teliti ditunjuk sebagai ketua pelaksana yang tugasnya mengkompilasi naskah-naskah Al-Qur’an yang masih berserakan tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya, Zayd dibantu Umar. Keduanya dengan ketat menetapkan bahwa kriteria yang diterima adalah laporan bacaan dan naskah Al-Qur’an yang benar-benar ditulis di hadapan Rasulullah dan disahkan langsung oleh beliau, tidak cukup hanya mengandalkan hafalan (la an mujarrad al-hifdz).
Perjuangan Menjaga Al-Qur’an
Karenanya jelas, upaya koleksi, kolasi, dan kompilasi al-Qur’an tidak digarap sendirian atau oleh satu dua orang saja, akan tetapi merupakan proyek yang melibatkan puluhan bahkan ratusan orang. Setelah berhasil dihimpun dalam mushaf utuh, naskah tersebut disimpan oleh putri Rasulullah yang bernama Hafshah.
Meski setelah Al-Qur’an dihimpun menjadi naskah utuh, masih terdapat banyak perbedaan bacaan. Menurut Syamsuddin, perbedaan tersebut wajar saja terjadi dan dapat dimaklumi mengingat Rasulullah membolehkan kaum Muslim pada masa itu membaca al-Qur’an menurut dialek suku masing-masing. Misalnya, Fakhr al-Din al-Razi dalam Mafatih al-Ghayb memberi informasi bahwa suku Kinanah, Bani Harits, Bani Rabi‘ah, Khath‘am, dan sebagian Bani ‘Adhrah tidak mengubah tanda gramatik suatu kata ganda meskipun dalam kedudukan marfu’, manshub, majrur. Seperti kata inna hadzaani dalam QS. Thaha ayat 63 yang secara gramatik seharusnya dibaca inna hadzayni.
Penyeragaman Dialek Al-Qur’an
Kebutuhan penyeragaman dialek bacaan Al-Qur’an baru muncul ketika Utman bin Affan menjadi Khalifah. Pasalnya, perbedaan mengenai bacaan al-Qur’an telah menimbulkan keributan di tengah masyarakat. Al-Suyuthi dalam al-Itqan mencatatkan bahwa seseorang yang bernama Hudzayfah bin al-Yaman sempat meyaksikan sendiri perselisihan semacam itu, kemudian menyarankan kepada Khalifah Utsman agar melakukan standardisasi bacaan dan tulisan al-Qur’an.
Setelah itu dibentuklah sebuah tim ahli beranggotakan 12 orang pakar al-Qur’an dari kalangan Muhajirin dan Anshar, termasuk di antaranya Zayd bin Tsabit, Ubay bin Ka‘ab, ‘Abdullah bin ‘Abbas, Sa‘id bin al-‘Ash bin Sa‘id, dan lain-lain. Menurut Syamsuddin, apa yang dikerjakan oleh tim ahli ini tidak sebatas koleksi, kolasi, dan kompilasi, tetapi juga kodifikasi dan membuat standardisasi bacaan dan tulisan al-Qur’an. Melalui jasa mereka itulah al-Qur’an terpelihara sekaligus menyebar hingga sampai kepada generasi kita.
Kesimpulannya, Al-Qur’an sebagai satu-satunya kitab suci yang dengan tegas menunjukkan dirinya bersih dari keraguan (la rayba fihi), dijamin keseluruhannya (wa inaa lahu la-hafidzun), dan tiada tandingannya. Hal ini membuktikan bahwa kitab suci ini benar-benar datang dari Allah secara verbatim. Menurut al-Suyuthi, keistimewaan Al-Qur’an terletak pada metodenya (ushlub), keindahannya (balaghah), dan kabar gaib yang disampaikannya (mughayyibat).
Penulis: Ilham Ibrahim | muhammadiyah.or.id